Review Kartini 2017: Suara Perempuan Yang Dikungkung Status Sosial
Menonton film ini membuat saya menangis sesenggukan
sekaligus marah. Marah pada ketidakadilan di masa lalu dan betapa rendahnya
posisi perempuan di masa kolonialisme. Raden Ajeng Kartini berani
mempertanyakan hal tersebut meski pada akhirnya harus rela menerima pinangan
seorang bangsawan beristri tiga dan meninggal di usia muda pasca melahirkan
putra semata wayangnya. Film yang dibintangi Dian Sastrowardoyo ini begitu
menggugah hati saya agar lebih berempati kepada sesama perempuan.
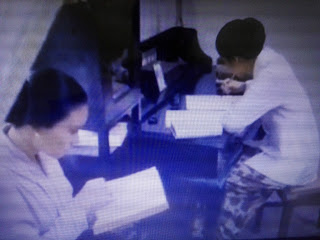 |
| Kartini, Roekmini, Kardinah yang sedang membaca (dok. pribadi) |
Film Kartini dibuka dengan adegan Kartini muda (Dian Sastro)
yang berjalan sambil jongkok. Itulah tata krama yang diajarkan bangsawan zaman
dulu. Seorang abdi dalem harus berjalan jongkok jika dipanggil majikannya dan
seorang putri bangsawan pun wajib berjalan jongkok jika dipanggil ayahandanya.
Kartini yang juga dipanggil Trinil sudah menunjukkan jiwa pemberontaknya sejak
anak-anak. Ia terlahir dari seorang rakyat jelata yang diperistri Bupati
Rembang masa itu. Karena ibu kandung Kartini bukanlah seorang bangsawan, maka
Kartini harus rela tidur terpisah dari ibunya dan diharuskan memanggil ‘Yu’
bukannya ‘Ibu’. Ibu tiri yang berdarah bangsawan, istri kedua Raden Mas Adipati
Ario Sosroningrat, yang berhak mengatur kehidupan rumah tangga dan juga
mengatur Kartini serta putri-putri lainnya.
Trinil menjalani pingitan semenjak masa menstruasi pertama. Ia
tak pernah melihat luasnya dunia di luar rumahnya. Ia pun hanya bisa mencicipi
pendidikan sampai usia 12 tahun saja, namun kecerdasan dan juga kemampuan berpikirnya tak bisa diremehkan.
“Tubuh bisa hancur dimakan tanah atau dibakar di atas kayu
bakar, tetapi pikiranmu tidak ada batas waktunya.” Itulah yang dikatakan
Sosrokartono, kakak kandung Kartini yang menginspirasi adiknya supaya tidak
berputus asa meski hidup dipingit.
 |
| Kartini dan sahabatnya Nyonya Ovink Soer (dok. pribadi) |
Konflik yang terjadi juga sangat menguras emosi. Ketika Kartini
dihalang-halangi untuk berdikari oleh Slamet, kakaknya sendiri dan juga
pernikahan Kardinah yang tiba-tiba. Ketiga gadis itu dipaksa untuk melepas
angan-angan mereka untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung pada status bangsawan dan juga tunduk di bawah pria. Kita juga tak hanya melihat pemberontakan Kartini pada kungkungan tradisi, tetapi juga belajar mengenai kesabaran dan arti pengabdian dari sosok ibu kandung Kartini yang diperankan Christine Hakim. Nasehat Yu Ngasirah itulah yang melunakkan Kartini agar mau dipinang.
Mungkin kiprah Kartini ini masih mengundang banyak
kontroversi, namun setidaknya kita menjadi tahu bagaimana perempuan tak
memiliki suara di masa lalu, lewat surat-surat Kartini kepada sahabat baiknya di
Belanda. Bukankah di masa kini pun, peran perempuan juga masih dibayang-bayangi
pemikiran patriarkhi di masyarakat? Betapa banyak pro kontra soal ibu bekerja sambil berumahtangga atau perempuan berpendidikan tinggi yang dianggap menyaingi laki-laki.
Film ini wajib ditonton masyarakat Indonesia agar pikiran kita bisa lebih
terbuka. Satu kalimat yang terus terngiang-ngiang di telinga saya setelah menonton adalah pertanyaan Kartini kepada seorang ulama yang berceramah di kediamannya.
"Apakah membaca itu hanya untuk laki-laki?"

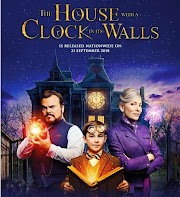




0 Komentar
Silakan berkomentar dengan sopan tanpa menyinggung SARA, ya ^_^